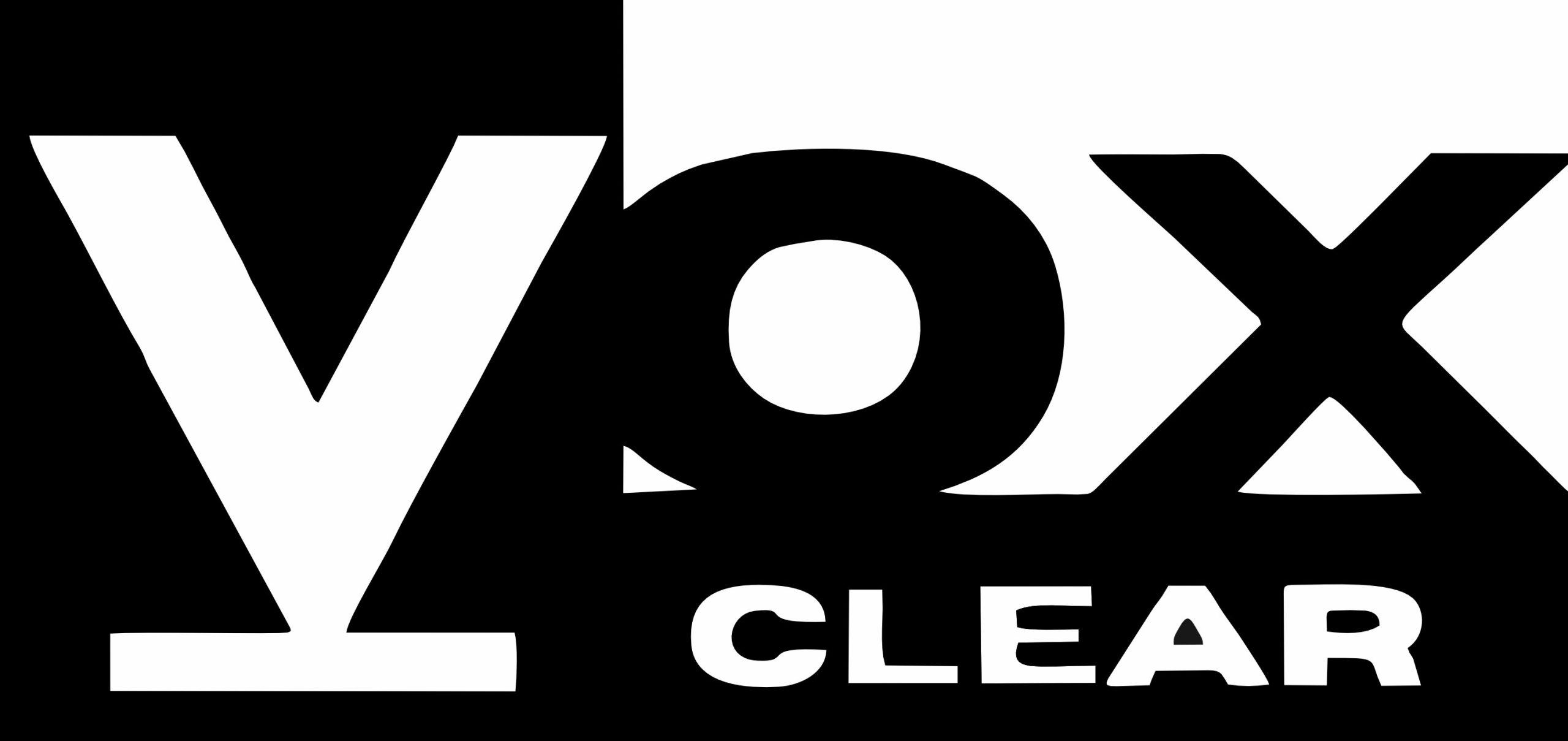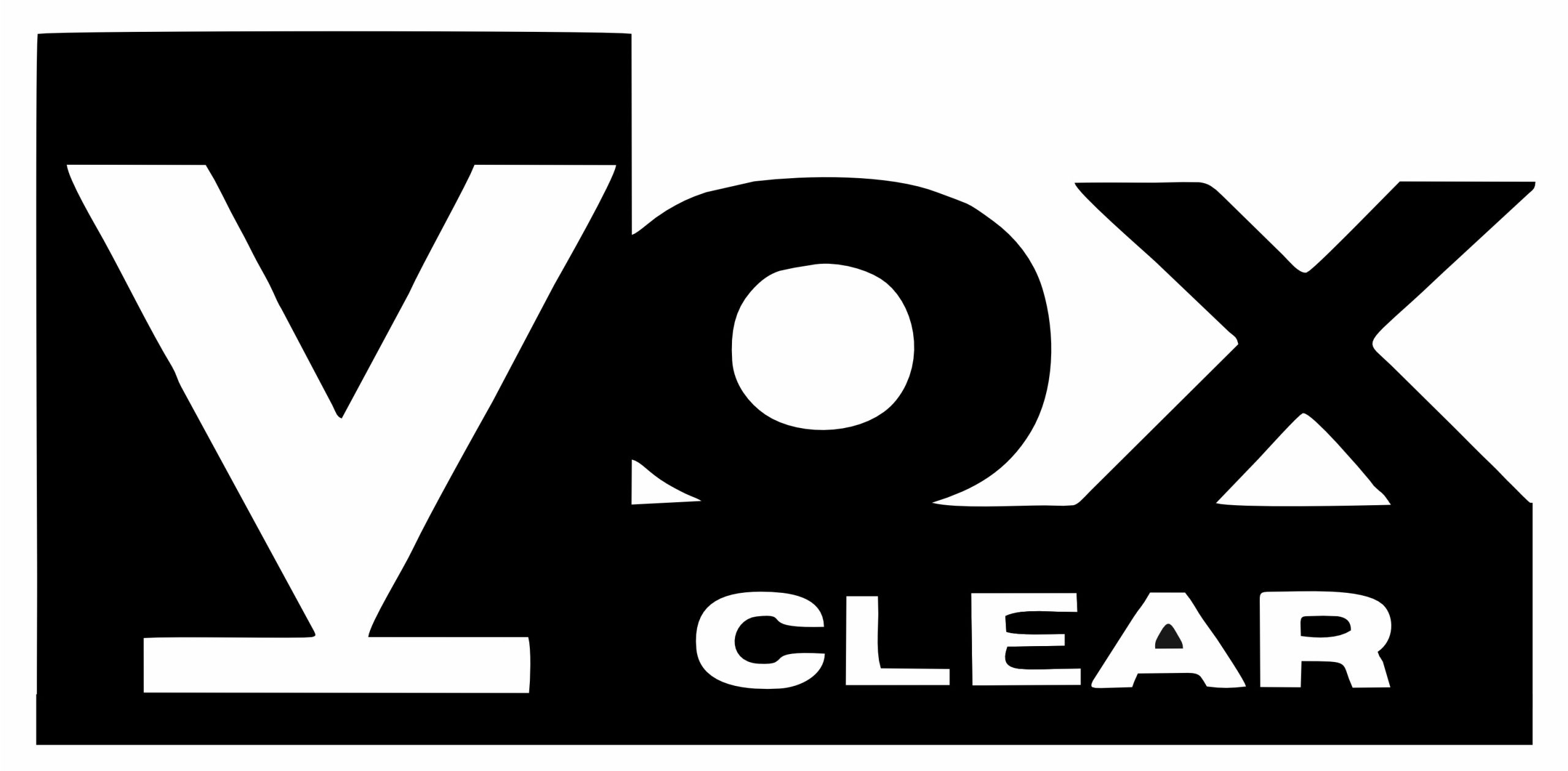Indonesia, sebagai negara dengan kekayaan budaya dan alam yang melimpah, memiliki ratusan masyarakat adat yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Mereka bukan hanya penjaga tradisi turun-temurun, tetapi juga pengelola sumber daya alam secara arif. Namun, eksistensi mereka terus terancam oleh kebijakan pembangunan yang kerap mengabaikan hak-hak dasar dan kearifan lokal.
Hak atas Tanah dan Sumber Daya Alam yang Terabaikan
Masyarakat adat memiliki hubungan spiritual dan historis dengan tanah leluhur yang menjadi sumber kehidupan mereka. Sayangnya, perluasan perkebunan, pertambangan, dan proyek infrastruktur seringkali merampas tanah tersebut tanpa kompensasi adil. Konflik agraria seperti di Kalimantan dan Papua menjadi bukti nyata ketimpangan penguasaan sumber daya.
Regulasi seperti UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria belum sepenuhnya melindungi hak masyarakat adat atas tanah. Pengakuan hukum terhadap wilayah adat masih parsial sehingga memudahkan korporasi menguasai lahan dengan dalih “kepentingan nasional”. Padahal, kearifan lokal mereka justru menjaga kelestarian lingkungan dari eksploitasi berlebihan.
Solusinya, pemerintah perlu mempercepat penetapan wilayah adat melalui program seperti Perhutanan Sosial. Selain itu, mekanisme Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) harus diterapkan agar masyarakat adat memiliki suara dalam pengambilan keputusan. Tanpa langkah konkret, konflik agraria akan terus memicu ketidakadilan.
Ancaman Kepunahan Bahasa dan Budaya Lokal
Bahasa dan budaya masyarakat adat adalah identitas bangsa yang tak ternilai. Data UNESCO menyebut, dari 700 bahasa daerah di Indonesia, 140 terancam punah, termasuk bahasa suku-suku pada suku kecil seperti, Togutil di Halmahera. Kepunahan ini diperparah oleh globalisasi dan minimnya upaya pelestarian.
Generasi muda masyarakat adat mulai meninggalkan tradisi karena tekanan ekonomi dan stigma “terbelakang”. Sekolah formal jarang mengintegrasikan muatan lokal sehingga anak-anak kehilangan ikatan dengan akar budaya. Dampaknya, pengetahuan tradisional tentang pengobatan, pertanian, dan mitigasi bencana ikut terkikis.
Pemerintah harus memprioritaskan revitalisasi budaya melalui kurikulum pendidikan berbasis kearifan lokal. Dokumentasi bahasa dan ritual adat oleh lembaga kebudayaan juga perlu diintensifkan. Jika tidak, Indonesia akan kehilangan warisan budaya yang menjadi pondasi kebhinekaan.
Marginalisasi dalam Pembangunan dan Kebijakan Publik
Masyarakat adat seringkali menjadi korban diskriminasi struktural dalam akses layanan publik. Data BPS menunjukkan bahwa komunitas adat di Papua dan Sumatra kesulitan mendapatkan layanan kesehatan dasar. Fasilitas pendidikan juga minim, terutama di wilayah terpencil.
Kebijakan pembangunan kerap meminggirkan partisipasi masyarakat adat. Partisipasi aktif masyarakat adat dalam perencanaan pembangunan adalah kunci solusi. Pemerintah perlu membentuk forum dialog inklusif dan mengalokasikan anggaran khusus untuk pemberdayaan komunitas. Tanpa itu, kesenjangan sosial akan semakin melebar.
Peran Masyarakat Adat dalam Mitigasi Perubahan Iklim
Masyarakat adat adalah mitra strategis dalam menghadapi krisis iklim. Praktik agroforestri suku Dayak atau sistem sasi di Maluku terbukti efektif menjaga keseimbangan ekosistem. Sayangnya, pengetahuan ini jarang diakui dalam kebijakan lingkungan nasional.
Alih-alih mendukung, pembukaan lahan untuk sawit dan tambang justru merusak hutan adat yang menjadi penyerap karbon alami. Deforestasi di Kalimantan dan Sumatra memperparah emisi gas rumah kaca, kontradiktif dengan komitmen Indonesia di Paris Agreement.
Integrasi kearifan lokal dalam kebijakan iklim harus segera dilakukan. Pemberian insentif kepada komunitas adat yang menjaga hutan juga perlu diperkuat. Dengan demikian, Indonesia bisa mencapai target net-zero emission tanpa mengorbankan hak masyarakat adat.
Masyarakat adat bukanlah penghambat pembangunan, melainkan mitra penting dalam mewujudkan kemajuan berkelanjutan. Melindungi hak mereka berarti menjaga keutuhan budaya, lingkungan, dan keadilan sosial. Pemerintah, korporasi, dan masyarakat harus bersinergi untuk menghentikan marginalisasi yang terjadi. Hanya dengan pengakuan dan penghormatan atas eksistensi mereka, Indonesia dapat benar-benar menjadi bangsa yang adil dan bermartabat.
Editor : Angela Wida Prastica